 |
| Ilustrasi: TEMPO/Mahfoed Gembong |
Oleh; Daniel
Randongkir*
Orang
Papua (khususnya kaum pejuang pembebasan) dewasa ini belum memahami dengan baik
permasalahan mendasar yang dialami oleh rakyat Papua. Sebaliknya sebagian kecil
individu yang perduli dengan persoalan Papua, justru jauh memahami persoalan
Papua. Fenomena ini menggambarkan bahwa ada kendala serius yang dihadapi oleh
rakyat Papua didalam memperjuangkan pembebasannya.
Kondisi
ini nampak jelas pada beberapa momentum yang dialami dan dilalui oleh orang
Papua. Misalnya dalam kasus Abepura Berdarah 2000, Wasior Berdarah 2001,
Pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua (Dortheys Hiyo Eluay), Penetapan UU
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Kuhsus dan Inpres No 1 Tahun 2003 tentang
Pemekaran Propinsi. Dalam momentum ini, reaksi pejuang Papua terlihat sangat
lamban dalam merespon, sehingga terkesan seolah-olah “membiarkan” momentum
tersebut. Sementara dipihak lain, berbagai pihak melancarkan protes atas sikap
Jakarta (Indonesia) terhadap rakyat Papua.
Fenomena
social-politik yang berkembang di Papua pasca Dialog Nasional 26 February 1999
di Jakarta, semakin membingungkan rakyat Papua Barat. Protes rakyat yang
terus-menerus diperjuangkan oleh berbagai pihak, semakin cenderung membias dari
keinginan rakyat. Banyak muncul organisasi perlawanan dan mengklaim diri
sebagai representasi rakyat, namun setelah berjalan, justru memicu krisis
kepercayaan di kalangan rakyat.
Trend
baru yang kini muncul dari aksi saling klaim, baik kaum oposisi (perlawanan
rakyat) maupun pemerintah, menunjukan gejala munculnya budaya totalitiarianime.
Dalam rangka memperoleh legitimasi rakyat, berbagai praktek politik diterapkan,
mulai dari eksploitasi ideologis sampai dengan manipulasi aspirasi. Realitas
yang muncul kemudian adalah kecenderungan mencari popularitas pribadi dari pada
memperjuangkan nasib rakyat.
Anatomy Masalah dan
Perjuangan Rakyat Papua Barat
Akar
persoalan Papua selama ini berawal dari proses integrasi Papua kedalam NKRI yang dianggap cacat oleh orang Papua. Sayangnya proses ini mendapat dukungan
politis dan juridis oleh masyarakat internasional, melalui payung PBB.
Akibatnya rakyat menilai bahwa telah terjadi manipulasi internasional terhadap
proses integrasi Papua.
Secara
ideologis, saya melihat bahwa akar permasalahan Papua berada pada keinginan
untuk bebas dari segala bentuk penindasan. Kondisi ini jelas terlihat pada perlawanan
rakyat yang muncul sejak pertengahan abad 19. Dalam fase ini, perlawanan rakyat
bertumpu pada ideologi mesianis dan pandangan primordial tentang “dunia baru”
(ibarat surga dalam konsep Islam, Yahudi dan Kristen). Perlawanan pada fase ini
diarahkan untuk menentang masuknya ajaran agama, terutama paham Kristen, serta
invasi bangsa Eropa dan Jepang ke Papua. Kita bisa melihat hal ini pada Gerakan
Manggarega di Fakfak (1900), Koreri di Biak (1942? 1945), Wage-bage di Paniai,
Nabelan-kabelan di Lembah Baliem dan sebagainya.
Pasca
integrasi perlawanan Papua lebih diarahkan untuk memisahkan diri (keluar) dari
RI, yang dalam pandangan rakyat Papua telah menerapkan sistem penindasan dan
eksploitasi terhadap SDA dan SDM di Papua. Rakyat beranggapan bahwa melalui
pemisahan diri (disintegration) dengan Indonesia, maka penderitaan rakyat akan
berakhir. Dalam fase ini perlawanan rakyat mulai bergeser pada ideologi global
tentang dekolonisasi dunia ketiga. Perlawanan rakyat pada fase ini diarahkan
untuk mengusir Indonesia (pemerintah maupun warganya) dari Tanah Papua. Hal ini
bisa kita saksikan dalam berbagai aksi perlawanan OPM (penyerangan maupun
penyanderaan), proklamasi kemerdekaan dan konflik SARA di berbagai daerah (terutama
dengan isu Papua vs Amber atau Islam vs Kristen).
Pasca
Revolusi Juli 1998, perlawanan rakyat mengalami pergeseran yang semakin jauh,
baik secara ideologis maupun intensitas aksi. Kondisi ini makin menunjukan
gejala regresi (kemunduran) perlawanan rakyat Papua. Dalam fase ini perlawanan
rakyat Papua bergeser pada isu global tentang HAM, Demokrasi dan Lingkungan
Hidup. Perlawanan rakyat pada fase ini lebih ditujukan untuk mendorong
terciptanya tata dunia baru yang dalam pandangan global akan mengurangi dampak
konflik di berbagai belahan dunia. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai aksi
kampanye ditingkat lokal, nasional dan internasional yang dilakukan oleh
berbagai pihak. Kecenderungan ini dapat kita lihat dalam berbagai pernyataan dukungan
dan simpatik yang ditujukan baik secara individu maupun institusi, terhadap
persoalan HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup di Papua.
Analisa dan Refleksi
Berdasarkan
realitas yang terjadi diatas, saya menganalisa bahwa ada beberapa hal yang
menjadi kendala utama dari aspek ideologis terhadap permasalahan dan perjuangan
Papua.
Pertama,
Degradasi Ideologi. Derasnya arus informasi, komunikasi dan interaksi social
yang makin mengglobal, telah mendorong terjadinya proses degradasi ideologi
Papua secara structural dan sistematis. Dampaknya jelas terlihat dari
pergeseran ideologi perlawaman rakyat Papua, yang awalnya ditujukan untuk
melawan penindasan dan eksploitasi, kemudian berganti menjadi “penciptaan tata
dunia baru”. Secara kritis dinilai seolah-olah kita sedang melaksanakan amanat
pembukaan UUD 45 untuk mewujudkan perdamaian abadi dan ketertiban dunia???
Sehingga perjuangan kita lebih bersifat pragmatis, karena hanya mengikuti
momentum yang sedang aktual.
Kedua,
Krisis Identitas. Menguatnya gejala totalitarianisme dikalangan “elite Papua”,
telah mendorong lahirnya sikap oportunisme dalam memperjuangkan nasib rakyat.
Beberapa individu telah mengeksploitasi institusi rakyat demi kepentingan
prestise dan popularitas guna mencari legitimasi rakyat. Akibatnya institusi
rakyat menjadi sarana penindasan, sehingga rakyat termarginalisasi dari
perjuangannya sendiri. Kondisi ini mendorong rakyat meng-generalisir semua
institusi rakyat sebagai musuh baru.
Ketiga,
Trikotomi Kelas. Kondisi ini lebih berdasar pada aspek ideologi dan pelaku
peristiwa pada ketiga fase tersebut diatas. Rakyat secara luas masih memiliki
keinginan untuk bebas dari segala bentuk penindasan dan eksploitasi, sementara
sebagian kalangan elite Papua masih cenderung memanipulasi dan mengeksploitasi
perlawanan rakyat demi kepentingan mereka. Hal ini mendorong munculnya kelas
sosial dalam masyarakat. Secara pyramidal, kalangan elite Papua berada pada lapisan
kelas teratas dengan porsi yang relatif sedikit, merupakan kumpulan para oportunis
Papua (para birokrat, “pejuang Papua”, dan pimpinan institusi rakyat), selama
ini terus-menerus memanipulasi aspirasi rakyat; pada bagian tengah (kelas
menengah) terdapat kelompok akademisi, aktivis, rohaniawan, LSM dan sebagainya
dalam jumlah yang sedikit lebih banyak dari kelas pertama, yang selama ini
mengeksploitasi penderitaan rakyat untuk kepentingan prestise dan
popularitasnya; sedangkan pada tingkat basis (grass root), terdapat kalangan
rakyat yang menderita dan tertindas, yang masih terus eksis memperjuangkan
nasibnya.
Berdasarkan
analisa diatas saya melihat bahwa letak permasalahan yang dihadapi oleh orang
Papua saat ini lebih banyak bersifat internal, sehingga saya mencoba memberikan
refleksi persoalan Papua dari aspek indeologi yang bertumpu pada beberapa
factor utama, seperti akan saya jelaskan dibawah ini.
Pertama,
Primordialisme. Orang Papua dengan jumlah suku yang lebih dari 250, sangat
rentan terhadap ancaman primordialisme. Gejala ini telah mulai merasuki semua
kelas sosial rakyat Papua, yang kerap muncul dalam tema putra daerah, penduduk
asli, tuan di negeri sendiri, orang gunung dan orang pantai, orang utara dan orang
selatan, dan sebagainya. Isu ini kemudian dikemas secara baik oleh kaum elite
Papua demi kepentingan sendiri, sehingga berpotensi menciptakan polarisasi
gerakan perlawanan rakyat. Kita bisa menemukan fenomena ini dalam momentum
pemilihan Gubernur/Bupati/Camat/Lurah/ Kepala Desa, rekrutmen PNS atau karyawan
swasta, penerimaan mahasiswa, fragmentasi faksi perjuangan Papua, dsb.
Kedua,
Pragmatisme. Perlawanan Rakyat Papua yang temporal, sporadis dan insidentil,
lebih disebabkan oleh mentalitas budaya peramu, yang masih dominan di Papua.
Tradisi ini dapat disimak dari pola gerakan perlawanan rakyat yang selalu
mengikuti momentum tertentu. Saya teringat salah satu point statement tim 100,
yaitu menolak partisipasi orang Papua dalam pemilu 1999 jika tidak dilakukan
dialog internasional. Reaksi pragmatis yang sama terjadi dalam momentum
penolakan pemekaran tahun 1999, peringatan tahunan 1 Desember 1999 dan 2000,
penolakan kebijakan Otsus Papua, dan penolakan Inpres 1/2003. Sikap demikian
membuat rakyat Papua mudah dipermainkan oleh kaum elite Papua dan pihak
Jakarta, karena kita selalu menunggu momentum untuk menyuarakan aspirasi kita.
Budaya peramu selalu mencari makan ketika merasa lapar, dan setelah kenyang
istirahat. Pola ini sama dengan perjuangan kita yang menunggu momentum baru
bereaksi jika tidak ada momentum tidak bereaksi.
Ketiga,
Feodalisme. Struktur klasik feodalisme tradisional masih dominan saat ini di
Papua, sehingga turut menciptakan hirarki kekuasaan yang hampir absolut.
Kondisi ini ikut memberikan peluang terciptanya arogansi dan eksklusifisme pada
berbagai institusi rakyat. Komposisi kaum feodal tradisional (tokoh adat) dalam
institusi rakyat, makin mengurangi peran kontrol dan kritik rakyat terhadap
institusi tersebut. Peluang ini dimanfaatkan oleh pihak Jakarta untuk
menjadikan kaum feodal sebagai tameng dalam meredam perlawanan rakyat.
Akibatnya ideologi rakyat terkooptasi oleh kaum feodal, sehingga muncul sikap
ketergantungan dan apatisme rakyat. Dalam tingkatan lebih lanjut, rakyat
melihat kaum feodal sebagai agen penindas dan ekploitator di Papua.
Kesimpulan
Berdasarkan
pemaparan diatas saya berkesimpulan bahwa: (1) Perjuangan Papua dewasa ini
tidak memiliki basis ideologi yang jelas, sehingga mudah dimanipulasi menjadi
alat kepentingan Jakarta dan agen penindasnya di Papua. (2) Bahaya laten
disintegritas revolusi rakyat Papua sedang berlangsung, dan secara sadar maupun
tidak rakyat Papua terseret kedalam scenario Jakarta. (3) Rakyat Papua
kehilangan daya kritik dan kontrol terhadap institusinya, sehingga mudah
terkooptasi.
(*)
Penulis adalah Alumni Antropologi Universitas Cenderawasih
Catatan; Tulisan ini di
posting 14 tahun yang lalu (Date: Wed, 19 Feb 2003 12:43:43 -0800 (PST)) dalam
mislis di yahoogroup yang mendiskusikan masalah-masalah Papua. Tulisan ini
masih layak untuk menjadi kajian dan refleksi bersama, oleh sebab itu redaksi
merasa perlu untuk memuat ulang.


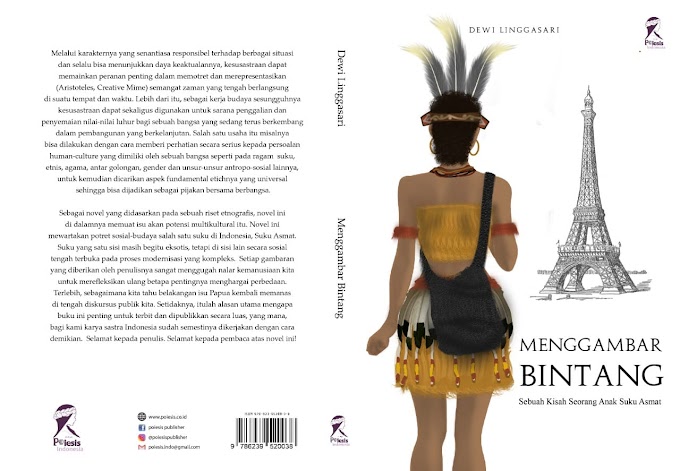





0 Komentar