Oleh Timoteus Rosario Marten
 |
| Doc. Kompasiana.com |
“Apa
pendapatmu tentang kematian?”
“Saya
tak bisa berpendapat. Intinya itu kehidupan manusia fana!”
“Tapi
secara spesifik bagaimana?”
“Seandainya imanmu tak goyah...!!!”
Potongan
dialog pembuka percakapan ini semacam teman perjalanan pulang antara Aku dan
Natalia suatu petang. Ketika itu riuhan Jayapura tak kami hiraukan.
Kami
pulang jalan kaki selepas menonton konser band Black Brothers. Jaraknya hanya selangkah saja dari kompleks
perumahan kami. Maka kami memilih berjalan kaki.
Dialog
kami makin ke sini ketika menyentuh persoalan serius. Persahabatan, cinta dan
kematian. Diselingi gurauan dan mop
Papua. Sesekali tawa berlomba ria dengan desingan mobil dan motor di tepi
jalan.
Waktu
menunjukkan pukul tujuh malam. Ayam-ayam mulai kembali ke sangkarnya. Sementara
bulan tak tampak di langit.
Belum
sampai lima ratus meter, dengan langkah yang mantap, Natalia berubah tingkah.
Raut mukanya seperti menyimpan cemas.
Ia
melihat-lihat di sekitar rumah penduduk. Napas panjang. Entah siapa yang
disasar.
Hamparan
tanah merah berdebu dan rumah-rumah warga tampak jelas ketika lampu-lampu rumah
bersinar terang. Natalia menengok ke kiri dan kanan. Aku makin penasaran.
“Kawan
sorry ee. Saya menunggu teman angkatan
semasa SMA. Nanti dia mengantarku pulang.”
Begitu
ujar Natalia dari balik bibir merah jambu sembari menggulingkan lengan
kemejanya. Bibir yang merona memikat jiwa yang merdeka.
“O,
ya santai. Tak masalah,” jawabku sekenanya.
Duarrttt!!!
Duarrr!!!
Tiba-tiba
bunyi motor dari arah belakang menghampiri kami. Pria jangkung berkaos hitam
dan celana pendek bersaku empat muncul.
Siapa
gerangan? Aku tak menaruh curiga atau prasangka. Sebab Aku harus memaklumi
bahwa Natalia adalah gadis polos, lugu dan tidak dungu. Ia adalah perwujudan
“pribadi yang lain” bagiku.
“Oh,
rupanya ini pria yang disebut Natalia teman angkatan!” Aku membatin.
Aku
lantas membuang senyuman padanya. Kerlingan mata tertuju pada aura sahaja di
balik cahaya petang.
Aku
melempar pandangan seakan tak mengetahui hubungan keduanya. Sementara dua
makhluk ini beradu pandang. Terbaca dari mimik ramah masing-masing. Memang
demikian adanya.
“Kawan,
kamu ojek saja. Sorry ya,” kata si
pria tadi sembari merogohkan saku celananya dan mendekatiku.
Sedianya
dia menanyakan kepada Natalia ihwal pertemanan kami. Entahlah soal yang lain.
Tapi lazimnya bila dua pria bertemu bersamaan dengan seorang perempuan, yang
satunya memperkenalkan diri. Pun sebaliknya. Atau Natalia yang memperkenalkan
Aku ke dia. Masalah selesai.
Sejurus
kemudian...
“Berapa
ojek, Bu?” tanyanya kepada seorang ibu paruh baya penjual minyak tanah di tepi
Jalan Ahmad Yani.
“Biasa,
to. Lima belas ribu,” jawab ibu tesebut dengan ramah sambil berkedip-kedip dan
mengangkat kedua alisnya.
Rupanya
itu bahasa kode. Tapi Aku tak menghiraukannya. Pikiranku terusik oleh
pertanyaan retoris. Semacam sikap skeptis dan rasa ingin tahu tatkala suatu
ketika Aku melakukan kerja jurnalistik.
Meski
kini Aku beralih profesi menjadi penulis lepas dan ghost writer, dan Natalia sebagai guru, toh naluri jurnalistik
masih melekat dan begitu dekat tatkala membaca drama ini.
Pria
jangkung misterius itu lalu memberiku ongkos ojek. Aku tak berkutik. Tapi tetap
mendelik.
“Sorry, kawan!” ujarnya melempar seutas
senyuman.
Aku
pun menerima uang pemberiannya. Namun uang itu hanya beberapa lembar saja.
Sepertinya hanya dua lembar uang kertas dua ribu rupiah.
Sementara
Natalia sahabatku membisu. Seakan dihipnotis malam. Ia berdiri mematung.
Sorotan matanya laksana elang laut yang menyimpan kalut.
Mengenakan
kem kotak-kotak dipadukan dengan celana levis abu-abu membuat perempuan ranum
itu tampak macho. Indahnya ciptaanmu, Tuhan!
Aku
tak habis pikir. Natalia tak pernah bercerita sebelumnya. Padahal semalam aku
bersamanya ke pasar malam. Seperti biasa kami pulang berduaan. Sesekali
bermesraan dan bertukar gagasan. Hingga pulang dinihari menuju rumahku. Malam
jadi milik kami pada satu atap tanpa sekamar.
Meski
dari balik gaunnya yang menampakkan lukisan mahasempurna karya pelukis Yang
Abadi, hati dan pikiranku tetap berfungsi. Mereka pasti sudah...
Tidak!
Aku mengerti batas kewajaran pertemanan. Suara hati terus menggema di jiwa
pengembara nusa tenggara.
Pria
jangkung itu lanjut men-starter
motorya. Asap membumbung menghambur dan bercampur debu. Disertai suara knalpot
yang dimodifikasi bagai motor pembalap.
“Lia,
Lia, sabar dulu!!
Aku
mencegahnya. Bukan bermaksud menahan agar dirinya berhenti berjalan. Toh waktu
terus berjalan. Itu pilihannya. Dan semua pilihan mempunyai risiko.
“Ada
apa, Roy?”
“Kalian
sudah cerai, kan?"
“Hushh!!
Mungkin terbawa mimpi, ya?”
“Aku
cuma memastikan saja, Lia. Aku tak mau menjadi saksi di meja hijau kelak."
"Apa
pedulimu?"
"Tak
lebih sebagai sahabat!"
"Ah,
ini duniaku dan bukan pilihanmu."
"Baiklah,
tapi..."
"Tapi
apa?"
"Aku tahu Mendra suamimu saban hari menjemputmu
di tempat kerja.”
"It is not your business," katanya
dengan bahasa Inggris dialek kampung.
Lalu
ia tertunduk malu-malu. Diam tanpa kata. Tapi memendam aneka persoalan. Seperti
Bunda Maria ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel dan menyimpan semua
perkara dalam hatinya.
Aku
kemudian berjalan pelan. Kuusap keringatku karena lelah berjalan lima puluh
meter menikmati panorama Jayapura City.
Ah,
lupakan saja pria asing ini. Toh tak menambah wawasan dan teoriku tentang
psikologi kepribadian.
Yang
ada di pikiranku cuma Natalia, Natalia dan Natalia. Namanya adalah napas dan
pikiranku.
Perempuan
ini agak rewel. Tapi menurutku ia komunikatif, cerdas dan punya wawasan terbuka.
Ia kerap membagikan pengalamanya. Namun malam ini tak pernah sedikit pun yang ia
ceritakan sebagaimana mestinya.
Sepuluh
tahun Aku mengenal penyuka warna cokelat ini. Begitu pula Aku dikenalnya
sebagai sahabat dan penghibur kala merana.
Seiring
berjalannya waktu, ia berubah tingkah. Biasanya jika punya masalah ia kerap
meminta pendapatku. Tapi tidak untuk malam ini. Jayapura jadi saksi.
Begitulah
manusia. Waktu terus berubah dan manusia pun tak mau ketinggalan. Tapi cerita
yang tercerai-berai ‘kan tetap abadi.
Kudekatkan
diri padanya. Kutempelkan telinganya di dekatku. Seerat ikatan tali kasih.
“Sebenarnya
Aku juga mencintaimu, Lia!”
“Hah?”
Lalu
ia menunduk haru. Tapi berat mengeluarkan senyuman. Sepenggal kalimatku seolah
bagai humor khas yang muncul secara spontan.
Ia
mendesah. Aku bisa menghitung desahan napasnya yang tak karuan. Berada di
antara dua pilihan dalam situasi yang tak menguntungkan adalah perkara yang
susah-susah mudah.
***
Sekejap
mereka menghilang. Suasana berubah menjadi tiga ratus enam puluh derajat. Ombak
pantai Kupang tak lelah menghantam cadas. Buih-buihnya menghempas jejak kaki
kami.
Segelas
kopi panas kuteguk. Penuh dalam. Bunyi bibirku yang menempel di mulut cangkir
memecahkan keheningan kedai kopi Tante Monika.
Seteguk
demi seteguk kuseruput. Dalam tradisi kami ihwal meminum kopi, menyeruput
jangan terlalu kebut. Maka maknanya akan menyata.
Kuambil
koran malam. Berita siang dari pojok kota tua, kedai milik Tante Monika. Kubaca
perlahan-lahan. Ada tanya juga.
Kolom
metro kota menyajikan berita yang sebenarnya lumrah di Kota Jayapura. Soal
perceraian.
Pengadilan
Agama menangani kasus-kasus perceraian sepanjang tahun 2017, sekitar seratus
delapan puluh kasus banyaknya. Ini lumrah di kota dengan heterogenitas dan
kesibukannya yang menggila.
Tapi
...
“Ada
apa, Anak muda?” tanya si ibu pemilik warung kopi.
“Tidak
ada masalah, Bu!” sahutku setengah menelan ludah.
Lagi
Aku membuka situs berita lokal. Kubaca perlahan-lahan dan penuh hati-hati.
“Perempuan dua anak yang
diketahui bernama Natalia tewas dilindas dump truck bersama lelaki paruh baya
di kawasan Taman Mesran.” Tulis situs ini pada teras beritanya.
“Ah,
Aku tak percaya. Ini hoax, berita
bohong.”
Semakin
kubaca, semakin benar informasinya, ketika beberapa menit yang lalu tertulis
berita kecelakaan bukan tunggal.
“Natalia!!!”
Natalia!!”
“Ada
apa, Anak?” tanya Tante Monika lagi.
Ia
kaget setengah mati. Apalagi Aku.
“Ceritanya
bagaimana, Roy?” Tanya Mendra setengah napas panjang dan berlari kecil ke
arahku.
Oh
Tuhan, Aku tak melihat Mendra dan dua anaknya, Mawar dan Eddoz yang muncul
bagai penampakan cahaya kemilau.
“Aku
baru datang mengeceknya, Kawan!”
“Sebelum
meninggal kamu bersama dia?”
“Tiga
puluh menit yang lalu!”
“Siapa
yang memboncengi dia?”
“Bosnya!”
“Hah,
apa?”
Sontak
Mendra mengayunkan tangan gempalnya untuk menjotosku. Tapi dengan cekatan juga Aku
mengendalikan diri dan emosiku. Tangan tak jadi mendarat. Meleset.
Mama,
Mama, Mama!!! Dua anak Natalia histeris. Teriakannya menjadi-jadi ketika
semakin yakin bahwa perempuan naas yang terbujur kaku adalah ibu mereka.
Tiba-tiba
kerumunan warga mengelilingi sepasang kekasih gelap ini. Tatapan bingungnya fokus
pada sosok kaku dan lemah. Aku mencium kaki Natalia sebagai penghormatan
terakhir. Ia berpelukan dalam kaku dengan
pria idaman lain itu.
Sementara
ban mobil truk pengangkut kayu dari perbatasan menggilas ganas. Ban mobil tak
hiraukan pelukan dua sejoli yang terjerat cinta sesaat tersebut. Cinta terbagi adalah
kawan maut.
Lalu
rombongan polisi kota berdatangan melakukan olah tempat kejadian perkara. Mata
Mawar, Eddoz dan Mendra mendadak sembab. Linangan air mata tak tertahankan dari
tiga anggota keluarga ini (*)
@Jayapura, 26 Mei 2017



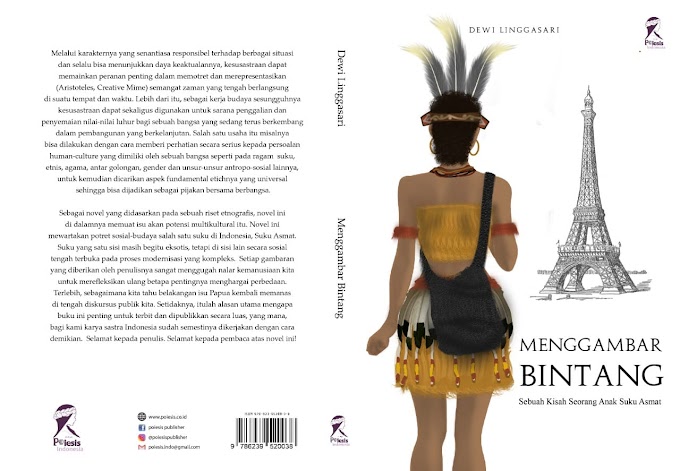





0 Komentar