Suasana kota tampak sebagai puing-puing
menghangus, jalanan yang lengang,
daun-daun yang merintih, sikap ketakutan serta saling curiga. Sementara umat
Kristen yang bertahan membangun kehidupan sendiri dengan sesama komunitas,
memiliki pasar tersendiri serta fasilitas sosial yang memiliki ciri berbeda
dengan umat Islam. Gardu pos dengan grafitti Istana Obet adalah milik umat Nasrani, adapun umat Islam membangun
gardu yang sama dengan goresan yang terbaca pondok
Acan. Obet adalah Robert dan Acan berarti Hasan, dua nama nyong --laki-laki muda remaja yang
sekaligus merupakan identitas dari Kristen dan Islam--
Dua
bocah berbeda nama itu justru tak mengerti sebab apa pertumpahan darah ini mesti
terjadi? Tempat bermain telah remuk menjadi puing, hitam arang, mereka tak bisa lagi saling berkejaran,
bermain kelereng, berselisih memperebutkan layang-layang putus serta tertawa
terkekeh-kekeh, karena hal-hal yang lucu dan menyegarkan. Anak-anak bahkan tak
tahu lagi bagaimana nasib kawan-kawan mereka, dimana sekarang Obet yang tinggal
di sebelah kanan rumah? Dimana pula Acan yang tinggal di dekat pasar? Semua
tercerai berai seperti satu nyiru beras yang dihambur ke tanah lapang oleh tangan-tangan yang
dikuasai benci.
Baik
Obet maupun Acan sama-sama menjadi yatim piatu ketika orang tua mereka tewas
dalam pertarungan demi pertarungan. Sementara Obet dan Acan yang menetap di
kampung lain sama-sama tenggelam di lautan ketika sebuah kapal yang sarat
muatan oleng diterjang gelombang kemudian miring, dibanjiri air laut,
menghilang dari permukaan air dalam sekejab bersama ribuan penumpang yang
menjerit ketakutan dijemput maut. Penggalan kapal, muatan serta tak satupun
jenazah penumpang ditemukan, kapal beserta seluruh isinya kembali kepada alam
ketika manusia-manusia menjerit nyaring bagi hak yang paling hakiki, yaitu hak
untuk hidup!
Apa
lagi yang mesti diceritakan? Bahkan orang-orang yang terlahir, bertumbuh,
dewasa, dan bersiap menjemput usia senja di tanah pusaka mesti berlari
serabutan menuju bandara, menumpang hercules ke Manado hanya dengan pakaian melekat di badan atau
sekedar celana pendek tanpa sepenggalpun harta benda. Seisi rumah hangus
terbakar, kampung halaman berubah menjadi puing-puing, menjadi debu. Mereka,
para pengungsi meninggalkan rumah tinggal dalam nestapa, amarah, dan ketakutan.
Mereka meninggalkan segala kenangan, sanak keluarga yang menjadi jenazah dan
tak mendapat penghormatan dalam pemakaman, yang tersisa kini tinggallah isak
tangis.
Ketika
kehidupan kota menjadi mati, pasar sunyi, tak ada lagi pedagang berani
menggelar jualan, karena khawatir keselamatannya terancam. Bahan-bahan makanan
dan kebutuhan sehari-hari sulit didapat, sehingga tehpun harus diminum dalam
keadaan pahit, karena tak mudah mendapatkan gula. Perlahan-lahan kerusuhan
mulai mereda, para perusuh itu kembali menyadari, bahwa kebutuhan hidup yang
paling penting adalah makan dan minum hari ini yang hanya dapat dipenuhi dalam
situasi aman. Pasar ramai oleh pedagang dan pembeli, karena keadaan
memungkinkan setiap orang untuk menjual dan membeli, mendapatkan nafkah serta
makanan hari ini.
Akhirnya setiap orang tiba-tiba
terduduk dan termenung, mengapa kerusuhan mesti terjadi? Fasilitas sosial
hangus terbakar. Sanak keluarga tewas, mengungsi, entah kapan mau kembali?
Penduduk yang mengungsi membangun rumah-rumah darurat dari papan kayu dengan
atap daun rumbia dan lantai tanah dengan sepetak bilik untuk beristirahat.
Mereka tinggal dengan komunitas yang dapat memberikan rasa aman dan
kepercayaan, sementara ketakutan akan
meledaknya kerusuhan menghantui setiap hari. Betapa mahal rasa aman!
Senja
itu turun dalam cahaya warna kuning keemasan yang jatuh menyinari wajah kota
yang muram diliputi puing. Suara sekawanan burung yang mencecet melintasi
langit kembali ke sarang bahkan terdengar sendu. Satwa itu harus kembali
membuat sarang baru, karena pohon tempatnya membuat sarang dan bertelur ikut
pula terbakar. Jalanan tampak sunyi, sesekali terdengar suara kendaraan
melintas kemudian diam, deru mesin hanya menyisakan asap yang segera musnah
dihalau angin. Pintu dan jendela rumah lebih cepat terkunci sebelum matahari
tenggelam dan gelap menelan seluruh cahaya keemasan.
Di
sudut rumah, di dekat perapian Tian termangu, ia tak dapat lagi menyalakan
kompor, karena persediaan minyak telah habis, ia harus kembali kepada fasilitas
alam untuk menghidupkan api bagi menu hari ini. Kerusuhan mulai mereda, akan
tetapi bukan berarti ia dapat bebas pergi kemana suka. Perkelahian demi
perkelahian sesekali masih terpecah, ia memilih jalan aman, berdiam di rumah.
Tian rindu pada anak didiknya yang lugu di taman kanak-kanak, tetapi bagaimana
ia dapat mengajar, bangunan sekolah telah retak dan coreng moreng. Ia hanya
sekali berani melintas di depan halaman sekolah dan tersedu melihat tempat
kerjanya nyaris menjadi puing-puing. Kejamnya
perang!
Seperti
kebanyakan orang Tian dihinggapi penyakit yang berawal dari ketakutan dan
ketiadaan peluang untuk bergerak bebas bagi kelangsungan hidup. Setiap orang
mengalami hambatan beraktivitas yang menyebabkan kepala menjadi lebih sering
berdenyut, tekanan darah menjadi terus naik atau menurun, dan bermacam keadaan
yang membuat badan menjadi tidak sehat. Tian rindu pula akan suasana pasar yang
meriah oleh beraneka barang dagangan, ia bisa menikmati kehidupan sebagai
keluarga berada untuk mendapatkan segala jenis barang yang ia mau dan iapun
menjadi senang. Kini, bahkan kesenangan-kesenangan yang paling kecilpun tak
bisa dinikmati, ia harus menjadi seekor pungguk yang merindukan bulan manakala
mengharap suara jerit atau canda ria dari anak-anak di halaman sekolah.
Tian
memijit-mijit kepalanya. Suasana rumah semakin muram tanpa aktivitas dari para
pekerja, mereka hanya berani menjual sembako yang diperoleh dengan susah payah
secara diam-diam kepada orang-orang yang benar-benar dikenal. Pintu dan jendela
bagian depan rumah telah hancur dan ditutup rapat-rapat dengan papan, menimbulkan
kesan rumah ini tak berpenghuni. Rumput ilalang telah naik tinggi, sarang
laba-laba berseliweran menggantung di langit-langit, pada malam hari lampu di
bagian depan masih tetap padam. Beta
telah tinggal di rumah hantu. Tian mengeluh dalam hati.
Perempuan
itu berhenti memijit kepalanya yang berdenyut-denyut ketika ia mendengar suara
muntah-muntah. Sejenak Tian tercenung, ia tak pernah merasa berkeberatan Betani
menetap di rumahnya dalam situasi seperti ini, keselamatan sahabatnya terancam.
Ia sungguh menaruh belas kasihan pada perempuan yang semula hidup aman dan
berkecukupan, tetapi dalam sekejab telah menjadi sebatang kara, tanpa tempat
tinggal. Perutnya yang mual dan menyebabkan ia harus berulang kali menumpahkan
seluruh isi di dalamnya, wajahnya yang semakin memucat, dan badannya yang lemah
membuat siapapun tahu. Betani tengah mengandung. Dimana ayah dari si jabang
bayi? Tian merasa dadanya sesak.
Ia
beruntung masih memiliki Orin dan tempat tinggal, ia masih mampu bertahan hidup
tanpa belas kasihan orang lain. Masih
lekat dalam ingatan ketika ia berpesta rujak sementara di dalam rumah keluarga
Betani tengah khusuk beribadah, ia tak
bisa melupakan seluruh kenangan akan prestasi dan sosok lembut seorang Betani.
Perempuan itu demikian sempurna. Suara calung dan gong yang memeriahkan adat
cuci kaki pada hari perkawinannya seakan masih nyaring terdengar. Betani layak
berbahagia bersanding dengan seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan
mencintai. Akan tetapi, bagaimana nasibnya kini?
Sejak
hari ketika Orin memondongnya dalam keadaan pingsan, Betani hanya berdiam diri
di rumah, ia membantu Tian mengerjakan urusan rumah tangga, memasak, menyapu,
dan mencuci piring yang kotor. Akan tetapi sebenarnya Betani lebih sering duduk
menyepi, meratapi nasib sekaligus memohon kekuatan supaya ia dapat menjadi ibu
yang baik bagi janin yang tengah dikandungnya. Tak pernah sekalipun ia
berselisih paham dengan Betani, mereka telah memahami satu sama lain sejak masa
remaja, dan kini setelah keadaan berubah menjadi demikian buruk dan
mencemaskan. Pengertian itu tak pernah berkurang. Tian memahami arti hak hidup,
ia selalu mencoba melakukan yang terbaik bagi perempuan itu. Tak ada yang
dimiliki Betani, kecuali dirinya dan tempat tinggalnya yang berubah menjadi
bangunan tua.
Tian
menyeduh sepoci teh, meraih dua cangkir gelas kemudian berjalan mendekati
Betani yang tengah terduduk menyandarkan kepala ke dinding. “Beta, minumlah teh
panas, mungkin bisa sedikit mengurangi rasa mual”, suara Tian mengejutkan
Betani.
“Oh
Tian, terima kasih, engkau seorang wanita yang sangat berbudi. Apa jadinya
nasib beta tanpa engkau punya ketulusan hati”, Betani tersentak, ia benar-benar
merasa lemah, lahir dan batin. Janin di dalam rahimnya membawa pengaruh yang
luar biasa, ia tak dapat melakukan banyak hal, ia diserang rasa mengantuk
berkepanjangan yang menyebabkan ia merasa sangat nyaman dengan berbaring dan berbaring.
Dimanakah Lambert, bapak dari si anak? Ia tak sempat merasa berbahagia dengan
kehadiran seorang mahluk tak berdosa yang kini tengah berlindung di dalam
rahimnya. Lambert tak dapat lagi merasakan apa-apa, si mati berurusan dengan
Sang Pencipta, si hidup berjuang bagi hari esok yang lebih baik setelah hari
lalu berserakan menjadi puing-puing bangunan. Betapa ingin Betani mengunjungi
rumah tinggalnya untuk melakukan yang terbaik bagi jenazah orang-orang yang
dicintainya, tetapi ia tahu situasi tak mengijinkan. Memperlakukan jenazah
dengan selayaknya adalah hal yang benar, akan tetapi yang lebih benar adalah
menyelamatkan diri atau lebih tepatnya menunggu waktu untuk melakukan hal-hal
yang diinginkan.
“Minumlah”,
Tian menuang teh ke dalam cangkir kemudian mengulurkan pada Betani.
“Terima
kasih”, Betani menerima cangkir, merasakan hangat teh meresap pada buku-buku
jemarinya. Ada perasaan takjub pada perilaku Tian yang tak pernah berhenti
mengulurkan kebaikan demi kebaikan. Sementara di luar orang saling membunuh dan
mengacau, maka di rumah ini ia justru mendapatkan segala perlindungan dan
secuil harapan untuk membangun kembali hidupnya yang telah runtuh menjadi
seonggok pasir
Apa
sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini?
Betani menahan genangan air
mata, ia telah menangis berhari-hari di sudut kamar kala gelap datang, ia
meratapi kedatangan Lambert, tetapi bahkan bayangan laki-laki itupun ia tak
dapat melihatnya. Sukmanya telah terbang menuju langit penghabisan, meninggalkannya
dalam keadaan sebatang kara. Betani meratapi pula rumah tempatnya berlindung,
kedua orang tuanya yang pasti telah menjadi arang, dan segala kenangan yang
telah dirampas hiruk pikuk kerusuhan. Akan tetapi, sampai lelah ia menangis
kesadaran membawa pada keadaan yang sangat nyata, bahwa ia tak punya apa-apa
kecuali kebaikan hati Tian dan Orin. Sampai
kapan mereka akan berbaik hati? Sampai kapan ia akan tinggal menumpang di rumah
ini? Sebaik apapun, mereka adalah
pribadi berbeda yang memiliki rencana hidup dan ia tak terlibat pula di
dalamnya. Pada akhirnya ia harus pergi, memunguti kembali kepingan harapan yang
tersisa dan membangun secara apa adanya.
Betani menatap jauh ke depan,
ia memang telah kehilangan ayah, ibu, dan suami. Akan tetapi ia masih memiliki
saudara Frederik yang telah menyelesaikan studi di Sam Ratulangi dan bekerja
pada sebuah kantor pemerintah di Manado dan adik tunggalnya, Tifani yang tengah
meneruskan studi pada universitas yang sama. Mereka pasti telah medengar perihal kerusuhan Maluku melalui
media cetak dan elektronik. Bagaimana nasib Tifani setelah orang tua tak mampu
lagi mengirimkan biaya kuliah? Mungkin Frederik masih bisa menanggungnya, akan
tetapi bagaimana perasaan mereka setelah berminggu-minggu mengalami putus
kontak dan tak tahu persis situasi apa yang terjadi pada rumah tinggal beserta
para penghuninya? Betani menghela napas panjang, pandangan matanya nyaris
mengabur, tetapi perempuan itu tahu, ia telah cukup lama menjadi beban pada
kehidupan sehari-hari rumah tangga Tian. Beban itu harus diakhiri, tapi apa
yang dapat ia lakukan dalam keadaan lemah seperti ini. Sambungan telepon
terputus, bagaimana dapat ia menghubungi Frederik atau Tifani? Tian tak pernah
bersedia menerima sepeserpun pemberianya, dengan jawaban, ia lebih membutuhkan.
Tian tidak kekurangan apa-apa dan tidak
rugi apa-apa pula. Betani tak menyangkal, betapa ia merasa bangga, terharu,
sekaligus takjub terhadap ketulusan hati suami istri yang kini tengah menjadi
induk semangnya.
“Bagaimana engkau punya kandungan
Beta?” Tian melirik Betani dengan pandangan sendu, ia tak bisa membayangkan
andai nasib itu terjadi pada dirinya, kehilangan seluruh anggota keluarga
ketika si jabang bayi membutuhkan kehadiran seorang bapak. Akankah ia mampu
bertahan hidup hingga hari kelahiran tiba?
“Beta punya kandungan baik-baik
saja, nanti setelah lewat bulan ke tiga baru mulai berkurang rasa mual. Beta
memjadi beban hidup yang berat bagi keluarga ini, maafkan beta Tian”.
“Aih, mengapa pula engkau
berkata serupa itu, beta tak rugi apa-apa engkau menjadi bagian dalam keluarga
ini, bukankah kita sudah berteman sejak masa muda remaja? Nanti setelah keadaan
membaik engkau bisa menyusun kembali rencana” Tian membelalakkan sepasang mata,
ia tak menyadari betapa wajahnya berubah menjadi lebih menawan ketika ia
berekspresi dengan segala kepolosan. Tangan wanita itu menggenggam jemari
Betani yang serasa tak memiliki lagi tulang belulang.
“Beta ingin melihat keadaan
rumah, jenazah mama, papa, dan Lambert belum diperlakukan sebagaimana mestinya.
Mereka punya roh belum tenang, masih menunggu adat pemakaman” Betani menyesap
teh hangat kemudian terbatuk-batuk, ia tak akan mampu melihat kondisi jenazah
itu, tetapi ia harus melakukan yang terbaik.
“Tunggulah sampai keadaan
benar-benar aman, nanti engkau bisa melakukan adat pemakaman”, Tian berusaha
menguasai getar suara, ia tak mampu membayangkan manakala Betani harus
berhadapan dengan situasi mengerikan, menyelenggarakan pemakaman ketika
jenazah-jenazah itu kini hanya tinggal tulang belulang dihinggapi belatung. Ia
harus melakukan sesuatu untuk meringankan duka hati sahabatnya itu.
“Kalian ada di sini?” tiba-tiba
tampak bayangan Orin berkelebat, laki-laki itu tampak tegap dalam pakaian yang
sederhana, celana jeans tua dan T shirt warna kelam, di tangannya
tergenggam kantong plastik. “Beruntung
sekali, hari ini beta mendapatkan sekantong langsat di pasar kilat, engkau
pasti suka Betani”, Orin mengulurkan kantong itu pada Betani yang diterima
dengan senyum tipis terkulum, Orin tahu betapa menyakitkan keadaan yang tengah
diderita Betani. Ia mengira oleh-oleh sederhana ini dapat sedikit menyejukkan
hati perempuan itu. Sementara ia duduk menyandarkan punggung di kursi, Tian
bergegas pergi ke dapur untuk mengambil cangkir bagi Orin, suaminya pasti kehausan setelah pergi melihat-lihat situasi
di kota dan dengan ajaib pulang membawa sekantung langsat.
Tian berniat segera menyerahkan
cangkir dan tatakan pada Orin, tetapi sampai di depan pintu langkahnya
terhenti, ia melihat pemandangan yang menyentak relung hati, menyakitkan
sekaligus mengharukan. Sejenak wanita itu berdiri limbung, Tian bahkan
kehilangan kesadaran dimana sebenarnya sepasang kakinya tengah berpijak. Apakah
ia tengah bermimpi?
Dalam jarak yang amat dekat
tampak Orin tengah meraih tangan Betani kemudian menggenggamnya erat-erat. Tian
berusaha untuk menyangkal, tetapi siapa dapat melawan naluri yang bekerja atas
dasar suara hati? “Beta sungguh prihatin atas keadaan yang terjadi pada engkau,
tak perlu merasa segan menetap di rumah beta. Pintu rumah ini bahkan terbuka
bagi engkau untuk selama-lamanya, andai engkau tak berniat pergi dari sini, tak
seorangpun dapat mengusik engkau. Kalau saja engkau hidup berbahagia dengan
Lambert, beta akan melepas engkau tanpa rasa sakit, tetapi coba lihat sekarang
engkau punya keadaan, bahkan untuk sekedar keluar berjalan-jalan engkau tak
punya keberanian. Katakan apa yang beta lakukan supaya engkau punya hati
senang?” Orin menatap Betani lekat-lekat, ia tak dapat membohongi perasaan
terdalam terhadap wanita itu, perasaan yang tak pernah dapat ditidurkan,
sekalipun ia telah menikah dengan Tian.
“Beta ingin pemakaman bagi
mama, papa, dan Lambert, beta harus cari tahu pula kabar Fred dan Tifa di
Manado”.
“Beta akan lakukan semua yang
engkau mau”, Orin mengecup telapak tangan Betani, badai seakan mengamuk di
dadanya. Di pihak lain Betani terpana, sepasang matanya menatap Orin dengan
takjub dan gamang, ia bukan anak-anak, ia tidak buta, tidak pula tuli, ia tahu
Orin tak pernah dapat berhenti berharap, sungguhpun ia telah terikat dalam
pernikahan sementara dirinya telah menjadi seorang janda muda. Orin memang tak
pernah berkata-kata, tetapi sikap dan tatapan matanya telah mengungkapkan
segalanya. Ia masih menjadi satu-satunya wanita yang dicintai, Betani seakan
terlambung dari kursi tempatnya menyandarkan diri, ia merasakan hembusan angin
menerpa dengan amat lembut, tetapi semakin lama berubah menjadi seakan taufan.
Betani sadar, ia adalah “orang lain” atau “duri dalam daging” yang berpotensi
secara aktif mengoyak perkawinan ini, perkawinan sahabatnya, Tian.
Dengan sepenuh kesadaran Betani
menarik kembali telapak tangannya, tiba-tiba udara berubah menjadi demikian
dingin, wanita itu menggigil, ia mencoba menenangkan dadanya yang bergemuruh
dengan meneguk teh panas. Selebihnya Betani mesti bersandiwara, ia harus
menjadi wanita baik-baik yang tak punya niat, kehendak, maksud atau perilaku
yang secara sadar dapat memisahakan keberadaan seorang suami dari sang istri.
Betani tahu betapa berat ia harus melakukan semua itu, tetapi adakah ia punya
pilihan kecuali bersikap sebagai wanita baik-baik? Tiba-tiba Betani sangat
merindukan kehadiran adik-adiknya, andai Fred bisa memungutnya dari puing-puing
rumah tinggalnya, ia tak akan berhadapan dengan Orin dalam keadaan seperti ini.
Betapa ingin ia menjatuhkan diri ke dalam pelukan Orin untuk mendapatkan
sejumput kekuatan, tetapi betapa tidak mungkin ia melakukan hal-hal yang tidak
berada pada tempatnya. Dan betapa norma-norma itu menyakitinya.
Betani tergagap ketika Orin
kembali meraih tangannya, menariknya berdiri merangkul kemudian membimbingnya
menuju halaman belakang rumah yang menjadi rimbun oleh dedaunan. Wanita itu
berniat berontak, tetapi ia sadar, ia tak berdaya. Betani tak pernah mengerti
betapa tak jauh dari tempatnya beranjak Tian terpaku bak sebongkah patung batu,
sisa tenaga masih bekerja sehingga cangkir dan tatakan dalam genggaman tak
jatuh berantakan. Tian dapat merampas tangan Orin supaya tak melingkar pada
bahu Betani, ia bahkan dapat mengusir wanita itu pergi hari ini juga atau
membisik pada para perusuh untuk menghabisi nyawa wanita itu. Akan tetapi, hati
kecilnya bersuara lain, apakah bila Betani menyingkir atau menjadi bangkai ia
akan dapat membunuh perasaan Orin yang terdalam?
Bukankah ia menikah dengan Orin
dalam sebuah kesadaran, bahwa satu-satunya wanita yang dicintai laki-laki itu
adalah Betani? Ia hanyalah seorang wanita yang menyediakan diri untuk mengobati
luka hati dengan sebuah akibat yang akhirnya harus ditanggung hari ini. Ketika
ia menyaksikan dengan mata kepala, Orin nyata-nyata tak dapat menidurkan
perasaan terhadap Betani. Langkah Tian surut ke dalam, ia merasa badannya
setengah terhuyung, dengan perlahan wanita itu mengatupkan daun pintu,
menyandarkan kepala, dan memejamkan mata rapat-rapat, ia berjuang melawan
gelepar hati yang menyentak-nyentak. Air mata wanita itu tergenang.
Di halaman belakang yang rimbun
oleh hijau dedaunan dengan setulus hati Orin masih merangkul Betani, ia tahu
betapa hancur hati wanita itu, diam-diam iapun merasakan kehancuran yang sama.
Apabila ia yang menjadi pengantin laki-laki pada perkawinan itu, apakah Betani
akan merasakan nasib seperti ini?Betapa
rumitnya jalan hidup!
“Segala yang pernah terjadi
pada masing-masing diri manusia adalah takdir, tak perlu disesali, kalaulah harus
menyesal janganlah berlarut-larut. Hari masih panjang, masih banyak yang harus
dikerjakan, engkau masih sangat muda. Suatu saat engkau akan dapat mengingat
segalanya tanpa kesakitan, ada hikmah pada setiap tragedi, yang penting adalah
bagaimana cara engkau memandang semua ini. Tidakkah engkau menyadari, bahwa
beta tetap menyayangiengkau?
Engkautidaksendiri, selamaada orang lain kitaakanmenjadibagiandarikehidupanini”
Orin menatapBetanilekat-lekat, iatakmenyadarikehadiransiapapun di rumahatau di
duniaini, iahanyaberduabersamaseorangwanita yang senantiasahadirdalamimpian,
iabahkanmelupakanTian. SekejabketikaiamenciumkeningBetani, Orin seakanmengapung
di dalamkabut. Di pihak lain Betani terpaku, iamerasa rapuh, demikian rapuh,
sehingga tanpa sadar ia menyandarkan seluruh kerapuhan dalampelukan Orin.
Waktupun diam membeku!
***
Orin menepatijanji,
iadatangmemeriksarumahtinggalBetani yang hanyatersisasebagaipuing-puing,
diam-diamtanganlaki-lakiitugemetar. Iaditemanitiga orang pekerja yang
setiadalamkeadaansusahdansenang. Di ataslangitgelapdikepungmendung,
bintang-bintangmenghilangditelankehitaman, suasana di sekitarsenyaptanpasuara, iaseakantengahtersurukkedalamliangpekuburan.
Bulukuduk Orin meremang, iaakanmenjumputsekumpulantulangbelulang
terbalut abu, iatelahmenyiapkankantungdanjugapetijenazah
yang dibuatsecarasederhanadanditinggalkan di rumah.
Cahayasenterberpendar,
Orin bergeraksangathati-hati, tidakmustahiliadapattertusukpakuberkarat,
pecahanbalok, kayuataubendakerasapapunbentuknya. Indra
pencium laki-laki itu menangkap bau busuk, ia telah menutup hidung dengan kain
tebal, tetapi aroma itu tetap tajam menyengat. Mereka berempat terus mencari
dan akhirnya tiga sosok tubuh yang telah
kehilangan identitas itu ditemukan. Orin tak mau mengingat saat-saat
ini, saat ketika ia berhadapan dengan situasi yang paling buruk dan mengerikan.
Orin melupakan segala ketakutan terhadap bermacam jenis hantu yang membayangi
sejak muda usia.Ia harus memenuhi janji teradap Betani, seburuk apapun keadaan
yang harus dihadapi. Dengan sangat hati-hati jenazah tak dikenal itu dimasukan
ke dalam keranda dikatupkan rapat-rapat dan diangkut dengan mobil bak terbuka
pada sepi suasana kembali ke kediaman. Jalanan dingin, tanpa suara, dan muram.
Betani dan Tian tengah
menunggu, malam seakan, lebih cepat melarut dari hari-hari biasa, desir
anginpun menyeramkan. Orin dan tiga orang pekerja menurunkan peti jenazah di
seputar tiga liang kubur yang telah disiapkan. Tak ada ibadah istimewa kecuali
doa yang terucap di dalam hati Betani, perempuan itu terdiam, ia tak dapat
membendung air mata. Segalanya berjalan dengan gagu dan menyatu dalam hitam
malam, bahkan gemersik anginpun terdengar menyakitkan. Waktu seakan berjalan
dengan lamban, detik jam menyentak hingga ke relung hati, Betani memejamkan
mata, ia merasakan genggaman tangan Tian erat pada dingin jemarinya.
Setelah pemakaman itu Betani
kembali tenggelam dalam doa di kamarnya yang sunyi, ia memilih sendiri, ia
melupakan segala kesibukan yang terjadi di seputarnya. Ia seakan tak menyadari,
bahwa kehidupan itu bahkan masih ada. Orin dan Tian membiarkan segala ulah
sikap Betani, dan Tian wanita bijak itu dapat memahami perasaan yang tengah
bergolak di dada suaminya.
Sore itu keduanya tengah duduk
di halaman belakang dengan sepoci teh panas serta cangkir di tangan, angin
berkesiur dingin. “Betani, maaf bila beta bertanya, tetapi bagaimana dengan
engkau punya kandungan? Bukankah anak yang bakal engkau lahirkan memerlukan
sorang bapak?” Orin membuka pembicaraan.
Diam.
Matahari hanya sebatas sinar
yang lesi lalu pudar memapas kelam, waktu seakan menggantung di langit-langit,
gagu, enggan beranjak. Sekelompok burung terbang mencecet membelah langit, Betani tersadar dari kebisuan. Ia tidak
sendiri, ia telah menjalani hal terpahit dalam hidup ketika harus kehilangan
orang-orang yang dicintai. Betapa kejam kenyataan, namun betapa ia telah cukup
mengutuki. Ada beban berat yang harus dipikul sepanjang masa, tak terelakkan.
Nasib bayi yang harus dilahirkan, mahkluk tak berdosa yang berhak akan segala
kasih sayang, terdengar suara helaan napas panjang.
Orin melanjutkan kata-katanya,
“Beta hendak mengatakan sesuatu, apabila kata-kata ini salah anggaplah beta tak
pernah mengatakan apa-apa, kalau kata-kata ini benar, itu yang beta kehendaki.
Akan tetapi, apa pun kata-kata itu engkau harus berbesar hati”.
“Apa yang hendak engkau katakan
Orin?”
“Betani, engkau punya bayi
memerlukan seorang ayah, sanggupkah engkau membesarkannya sendiri dalam keadaan
seperti ini. Apabila engkau tidak sanggup beta bersedia dengan setulus hati menjadi
ayah bagi bayi yang engkau kandung. Kata-kata ini sekaligus, bahwa beta
melamarmu”, suara Orin demikian tenang, datar, tanpa gejolak, tapi di telinga
Betani suara itu berubah menjadi tiupan taufan yang semakin lama semakin
menghembus dengan dasyat menggetarkan seluruh tubuhnya. Tangan perempuan itu
gemetar, diam-diam ia berpegang pada sandaran kursi. Betani tak mampu mengucap
sepatah kata jua. Hatinya merasa demikian takjub, sanggupkah ia menampik
lamaran Orin dalam keadaan ia tak memiliki sesiapa untuk menyandarkan
punggung, juga bapak bagi janin yang
tengah ia kandung. Kejujuran hatinya tak akan sanggup menolak lamaran itu, tapi
Orin terikat perkawinan resmi dengan sahabatnya.
Apa sejatinya seorang sahabat,
kalau diam-diam ia berbuat khianat? Sanggupkah ia menjadi orang ketiga dalam
kehidupan Tian, adakah seorang istri yang demikian tulus menerima kehadiran
istri kedua sang suami? Samar-samar Betani tersenyum, sekarang bukan lagi zaman
ketika seorang perempuan hanya bagian kedua dalam perkawinan, bukan lagi objek
yang bersiap diam, apa pun yang akan dilakukan sang suami, termasuk bila ia
menikahi lagi seorang wanita demi janin yang dikandungnya. Ah, kehidupan....
Betani menarik napas
panjang berulang kali, ia tahu betapa tegang Orin akan jawaban itu, tetapi
mulut Betani terkunci, ia tak sanggup mengatakan apa-apa, ia tak sanggup
menolak tak dapat pula menerima, hatinya buntu. Di balik tirai Tian merekam
pembicaraan itu dengan tenggorokan tercekat, ia tak terkejut dengan kata-kata
Orin, meski ucapan itu tak berbeda dengan bilah pedang yang mencabik ulu
hatinya dengan kejam. Dengan perlahan Tian menghela napas, ia merasa begitu
tegang menunggu jawaban Betani. Kata-kata apa gerangan yang akan diucapkan
wanita itu?
**
|
B
|
ahkan malam yang paling panjang sekalipun akan
sampai jua kepada fajar, bukankah semesta demikian arif mengedarkan sinar?
Susah senang seperti halnya gemuruh air laut yang sesaat pasang kemudian surut.
Kalaulah fajar tak sepenuhnya disepuh cahaya, cukuplah kilau sinar itu membuat
Betani tersenyum dan menghembus napas lega, ia akan mengakhiri semua bencana
ini dan memulai kehidupan yang baru. Hari ini Tian mengulurkan sepucuk surat
dalam sampul yang kumal, sampul itu tak banyak berarti, yang lebih penting
adalah isi di dalamnya. Dengan tergesa
dan bersemangat Betani membuka surat itu, ia segera mengenali tulisan tangan
Frederik, di dalam surat itu terdapat pula kertas karbon yang menyimpan
sejumlah uang. Isi surat itu singkat saja.
Kakak,
Kutunggu hadirmu
di Manado, ada sejumlah uang untuk membeli tiket. Awali suatu kehidupan baru.
Salam,
Frederik
“Surat
dari kau punya adik?” Tian membuka pembicaraan.
“Ya,
beta pernah melayangkan surat ke Manado, beta kira surat itu tiada pernah
sampai, keajaiban yang dapat membawa surat beta punya adik hadir di sini.
Terima kasih Tian”, Betani memandang Tian dengan rasa terima kasih tiada
terperi, ia telah cukup meminta dari perempuan ini dan cukuplah segalanya
sampai di sini.
“O
ya, beta mendengar pula pembicaraan Orin dan engkau tempo hari, engkau tiada menjawab
sampai hari ini. Andai engkau menerima lamaran Orin, beta tiada pula
berkeberatan, demi bayi yang tengah engkau kandung. Sungguh”, Tian menatap
wajah pucat Betani, ia bahkan tak bisa menerka bagaimana sebenarnya gejolak hati,
susah, senang, gelisah atau merana, ia hanya berkehendak untuk mengikuti kata
hati, apa pun jawaban Betani.
Sejenak
hening mengggantung di tengah ruangan seakan udara yang bergerak diam-diam,
namun bersiaga untuk menerkam. Betani duduk membantu, ia menatap Tian dengan
pandangan asing, ia tak menyangka, bahwa Tian mendengar pembicaraannya dengan
Orin tempo hari. Suatu pembicaraan yang pasti sangat menyakitkan hati
--seandainya ia adalah Tian-- dapatkah ia mendengar pembicaraan itu tanpa
sedikit pun kemarahan? Kali ini Tian bahkan merelakan diri bagi kesanggupan
jawaban itu, bagi bayi yang tengah ia
kandung. Adakah perempuan ini tengah
bersandiwara?
Betani
tersenyum tipis dan hampir saja tertawa, tapi niatnya urung, ia menangkap
kesungguhan pada tatapan mata Tian. Perempuan itu tidak sedang bermain-main,
bulu kuduk Betani meremang, ia sadar diam-diam tangan yang menggenggam sepucuk
surat gemetar. Betani tidak yakin siapa kiranya Tian, apakah ia seorang wanita
yang benar-benar baik? Atau hanya beracting di atas theater kehidupan setelah nasib yang “malang”, atau hanya
seorang hamba Tuhan yang menaruh belas kasihan, karena di hadapnya ada pula
seorang wanita yang tengah tersungkur di hajar kerasnya kehidupan?
Diam
masih menggantung, memecah tak berapa lama kemudian ketika Betani menghela
napas dalam-dalam. Bukankah ia telah menemukan jawaban? Perempuan itu berdiri,
menggenggam sepasang tangan Tian, menatapnya dalam dalam, kemudian memeluknya.
Tak terasa sepasang mata Betani basah, karena isak tangis.
***
Hari
ini --seperti halnya hari-hari yang lalu-- penerbangan Merpati Manado-Kao
datang terlambat, gerimis merinai dalam curahan air yang lembut seakan cucuran
air mata seribu peri. Desakan angin yang menghembus kemudian mengacaukan
sekumpulan mendung hitam, memberi celah bagi surya untuk berpijar seakan pertanda bagi warna
semesta, langit tak selamanya gulita. Betani duduk tenang di ruang tunggu
dengan tas dan kopor yang sudah terisi dengan benda-benda penting yang pasti
diperlukan, hati perempuan itu sudah bulat, ia harus berpamit meninggalkan
kehidupan di kampung halaman yang sudah hancur lebur. Hari esok masih ada, ia
masih bisa medapatkannya, demikian pula dengan harapan bagi janin yang
dikandungnya. Bukankah air selalu menetes ke bawah kemudian mencari bentuk dan
karakter sesuai dengan wadah yang
tersedia? Apa yang mesti ditakutkan kecuali ketakutan itu sendiri, dan ia telah
melampaui apa sebenarnya takut?Akhirnya, ia harus berjuang untuk mendapatkan
kembali keberanian. Hidup masih masih sebuah tantangan.
“Engkau
bersungguh-sungguh hendak pergi Betani?” Suara Orin serak, ia seakan tengah
dihadapkan saat-saat yang amat sulit, karena akan kehilangan sosok yang
dicintai untuk selama-lamanya. Betapa tidak mudah kehilangan, karena waktu akan
membenturkan hati ke dalam hampa tanpa kata. Ia masih memiliki sisa kekuatan
untuk membendung air mata, ia seorang laki-laki, ia tidak perlu menangis.
“Kalaulah
beta masih bisa bertahan tinggal di tempat ini, tapi betapa tidak mungkin.
Biarlah yang sudah terjadi berlalu, manusia menjemput takdirnya sendiri”.
“Jadi,
engkau menolak lamaranku?”
“Andai
waktu bisa diputar undur, tetapi betapa tidak mungkin. Sepenuh hati beta
menyayangi engkau Orin, tetapi biarlah rasa sayang itu hanya ingatan, karena
beta mesti pergi dan tak akan pernah melupakan engkau. Beta akan mengenang
engkau berdua selamanya, kalau anak ini terlahir laki-laki akan beta kasih nama
Orin kalau terahir perempuan akan beta kasih nama Tian. Ijinkan beta mengenang
kalian berdua dalam damai selamanya, bukan dalam kesakitan”.
Lalu terdengar gemuruh suara
pesawat mendarat, sekitar landasan pacu adalah kesunyian dan rumput ilalang
yang masih basah setelah rinai gerimis, selebihnya rimbun hutan yang tiada
bertepi. Sekalian penumpang turun, kemudian penumpang yang sudah bersiap
berangkat beranjak menuju ke pesawat. Orin merasa kesunyian yang lengkap,
kepedihan tanpa batas, dan hampa yang sempurna ketika Betani menggenggam tangan
kemudian mencium sepasang pipinya. Ia tak hendak melepas perempuan ini pergi,
tetapi harus, Orin hanya melihat bayangan yang bergerak kabur ketika Betani
berpelukan dengan Tian kemudian keduanya melambai mengucap salam perpisahan.
Sesaat kemudian pesawat udara
kembali menggeram dan bergemuruh membawa sosok Betani dan penumpang lain
terdiam di atas kursi terikat sabuk pengaman. Dari jendela pesawat Betani dapat
melihat Orin berdiri dengan gontai dan wajah sekelam mendung, di samping Orin
adalah Tian. Perempuan itu berdiri dengan ketabahan dan raut wajah sulit
dilukiskan. Dada Betani terasa sesak, lehernya tercekik, pandangan matanya
perlahan menjadi bayang-bayang ketika ia tak dapat lagi membendung air mata.
Terlalu banyak yang harus ditinggalkan, tapi adakah ia akan sanggup menetap?
Sebuah raungan mengawali Twin
Otter itu meninggalkan landasan, terbang seakan merpati memapas langit dalam
kesungguhan. Betani memejamkan mata, kalaulah ia seorang penyair, ia bahkan tak
akan pernah mampu menyusun kata-kata bagi perpisahan ini. Iapun merasa bobot
tubuhnya mengapung dan melesat ke dalam ketinggian tanpa ujung. Bayangan Orin
dan Tian menghilang ditelan kabut.
Di tepi landasan pacu Orin
masih mematung dalam rasa gamang, ia menatap laju gerak pesawat dengan rasa
berat dan bahu serasa ditimbun bukit. Kesiur angin serasa teramat dingin
menggelisahkan, lutut Orin menggigil. Tubuhnya limbung dan nyaris rubuh, tetapi
tiba-tiba ia merasakan genggaman hangat pada telapak tangannya yang gemetar.
Genggaman yang tiba-tiba memberinya kekuatan dan satu kesadaran mutlak, ia
tidaklah benar-benar sendiri, ia bahkan tidak kehilangan apa-apa. Orin menoleh
dan tatapannya segera bertautan dengan sepasang mata Tian. Sepasang mata yang
ditopang kekuatan dan ketabahan tiada tara, masihkah ia harus bertanya tentang
cinta? Apa yang tidak diperoleh dari Tian, ketika Betani tak dapat memberikan
apa-apa, bahkan ketika ia telah memintanya.
Betapa cepat perasaan manusia
berubah, antara ada dan tiada, antara harap dan ketakutan, antara kesendirian
dan kebersamaan. Segalanya hanya lelaku seakan perubahan warna dari gelap
menuju terang, dari badai menuju reda --pun si-aku tak boleh berubah mencapai
tuju. Di atas langit perlahan disepuh cahaya, sisa gerimis memanggil bianglala
di batas angkasa menyudahi kelam. Orin masih terpaku tatapan matanya demikian lekat , sehingga ia
dapat melihat bayangan pelangi melengkung pada sepasang bola mata Tian seakan
tujuh warna yang membias dari selendang sang bidadari maya.
Selesai
Agats – Asmat, 22 Mei 2012
Catatan dari perjalanan ke
Halmahera





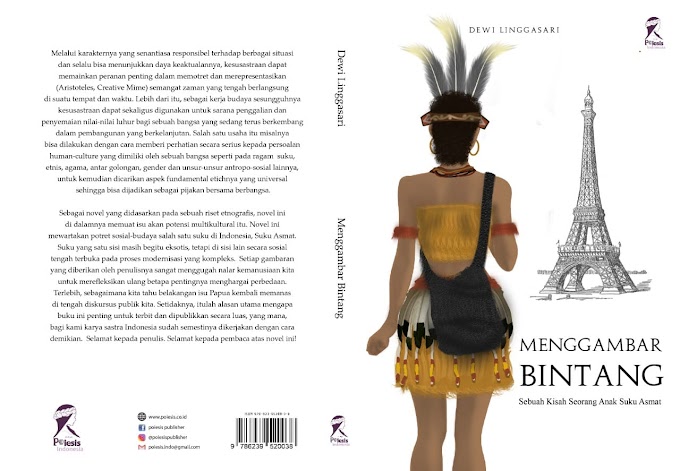


0 Komentar